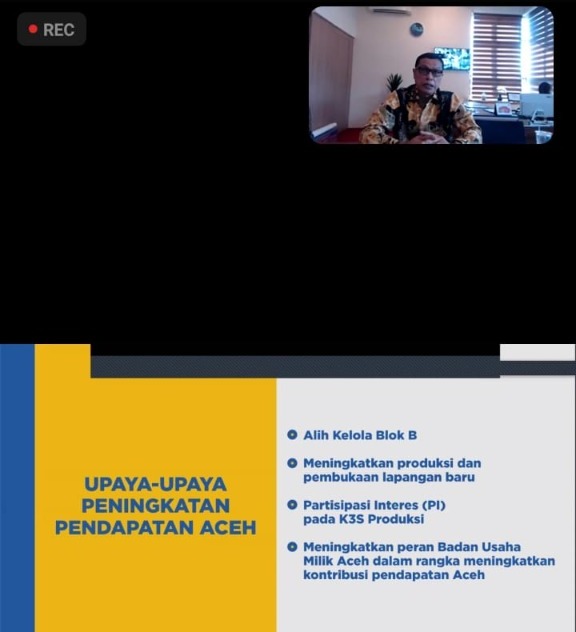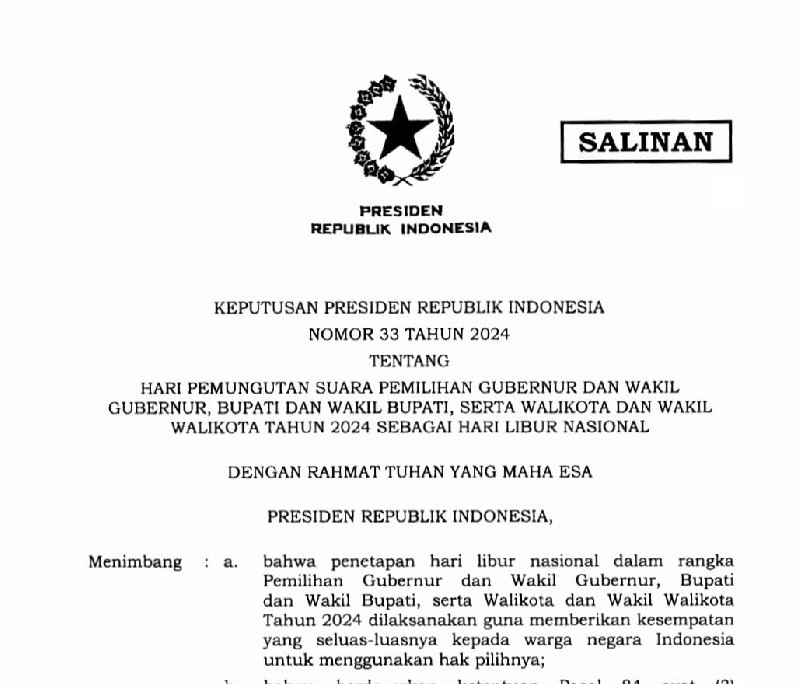Konflik Tanah Bukan Ulah Perusahaan, Tapi Karena Negara?
Font: Ukuran: - +
Reporter : Akhyar

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Aceh, Muhammad Nur. [Foto: IST]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Peristiwa saling klaim lahan antara warga dengan pihak perusahaan atas nama tanah Hak Guna Usaha (HGU) masih terjadi dimana-mana, termasuk di Aceh.
Terkadang klaim kepemilikan tanah ini kejelasannya juga simpang siur. Dalam artian, warga mengklaim lahan tersebut sebagai tanahnya, sedangkan pihak perusahaan menyebut bahwa luas tanah cakupan wilayah kerjanya itu masuk ke dalam HGU.
Bahkan terdapat juga fenomena para warga yang mencaplok tanah HGU karena ketidaktahuan. Akibat warga melihat tanah HGU yang tidak difungsikan, warga menganggap tanah ini kosong kepemilikan sehingga dimanfaatkan untuk berkebun atau membangun rumah dan pemukiman.
Padahal untuk menghindari konflik tanah, pihak pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI sudah mengeluarkan pengaturan mengenai HGU, mulai dari pemetaan berapa luas cakupan HGU hingga segala macamnya.
Tetapi tetap saja, perang klaim tanah ini tak kunjung usai. Tau-tau para warga sudah diusir saja. Kasus-kasus konflik tanah di Indonesia hingga kini masih saja terjadi.
Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Aceh, Muhammad Nur, ia mengatakan permasalahan sengketa lahan di Indonesia sudah menjadi persoalan yang lumrah terjadi.
Hal ini disebabkan karena negara menganggap seluruh tanah dengan tanpa kepemilikan yang terdaftar dianggap sebagai tanah negara, walaupun di tanah itu sudah ada penghuninya.
Menurutnya, penetapan batas wilayah pemukiman, wilayah hutan dan lahan di Indonesia tidak lah singkron.
Penyebabnya, kata dia, karena aspek sejarah bangsa ini dimana orang-orang terdahulu adalah bangsa pengembara atau orang yang berpencar ke pelosok hutan dan lahan dan menetap di sana.
Dalam perkara ini, lanjut dia, sejak dulu pengakuan pemerintah terhadap keberadaan masyarakat di sekitar hutan dan lahan tidak pernah dilakukan organisir.
"Pemerintah bisa jadi abai terhadap keberadaan orang di tanah-tanah tertentu sehingga pada generasi berikutnya tanah tersebut dianggap sebagai tanah kosong," ujar Muhammad Nur kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Sabtu (2/10/2021).
Berkenaan dengan cara pandang tanah, Muhammad Nur mengatakan, Indonesia sudah melewati tiga periode cara memandang sebuah tanah.
Pertama, sejak masa dinasti (kerajaan) di Indonesia, cakupan wilayah tanah dikuasai di bawah naungan kerajaan. Sehingga kepemilikan tanah bagi warga jaminannya di dapat secara hukum adat.
Kedua, semenjak jaman kolonial Belanda menjajah Indonesia, Belanda menganggap tanah jajahannya itu sebagai tanah miliknya. Sedangkan warga dianggap buruh kerja paksa semua meskipun lahan perkebunan atau tanah dibangun rumahnya itu milik pribadi yang didapat secara adat sejak kerajaan.
Ketiga, pasca Indonesia merdeka. Setelah merdeka, Indonesia menganggap semua cakupan wilayahnya sebagai milik negara. Di era ini, ketentuan kepemilikan tanah pribadi atau klaim bahwa sebuah tanah itu adalah milik warga dengan cara membuat sertifikat tanah.
Pemerintah, kata dia, memandang lahan atau tanah di luar pemukiman warga sebagai tanah milik negara. Misalkan seperti hutan lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan area-area lainnya.
Sedangkan para warga, lanjut dia, yang kebetulan berkebun di luar pemukiman itu memandang tanah tersebut sebagai tanah miliknya yang didapat secara adat. Misal pernyataan warga ialah klaim tanah itu milik pribadi karena secara adat didapat secara turun-temurun, walau terkadang tidak ada pembuktian secara dokumen atau notaris surat tanah.
"Nah, saling klaim tanah ini antara masyarakat adat dengan kepemilikan negara yang kemudian tidak singkron dari sejak jaman kolonial dulu," ungkapnya.
Reforma Agraria Terlambat?
Dalam upaya pencegahan konflik sengketa lahan, Indonesia mengeluarkan kebijakan Reforma Agraria. Di mana semangat Reforma Agraria ialah untuk meluruskan ulang atau memetakan ulang tanah terlantar atau tidak terurus.
Sehingga dengan Reforma Agraria dimulai lah kembali pemetaan batas-batas tanah wilayah HGU dengan batas tanah kepemilikan desa.
Namun, menurut Direktur Walhi Aceh itu, pemetaan batas HGU dengan batas kepemilikan warga dianggap sudah terlambat.
Karena, kata dia, tanah HGU itu sudah berdiri tegak jauh melebihi usia Indonesia merdeka. Mekanismenya ialah HGU itu telah turun-temurun dari era kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka.
M Nur menjelaskan, di saat wilayah tanah HGU yang tidak difungsikan oleh negara karena tidak ada usaha kerja yang beroperasi di sana, maka para warga kadang juga menjadikan tanah HGU itu sebagai pemukiman untuk menetap atau tanah sekedar berkebun.
Ia menuturkan, semisal jika tanah HGU milik negara saat belum ada usaha kerja masuk, pihak pemerintah sudah tahu kalau di HGU itu terdapat warga yang tinggal. Akan tetapi di saat investor masuk untuk meminta izin usaha lahan HGU, maka pemerintah menganggap warga yang tinggal di wilayah sana sebagai penghuni ilegal dengan dalih tidak ada pembuktian dokumen tanah kepemilikan.
Sehingga, kata dia, sengketa tanah yang lumrah terjadi ini pemicunya bukanlah perusahaan yang mendapat izin HGU melainkan konflik yang dipicu oleh pemerintah itu sendiri.
"Konflik tanah ini diciptakan oleh negara, bukan oleh pengusaha," pungkasnya.
Berita Populer







 Sebelumnya
Sebelumnya